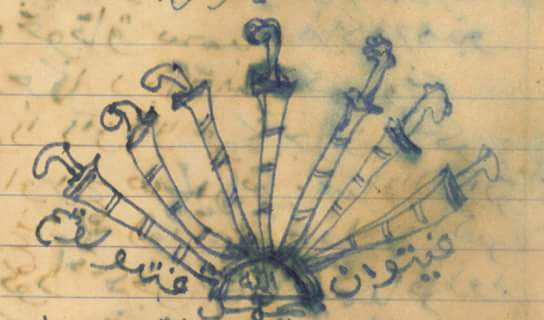Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul ‘Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat’.
Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.
***

Latar Belakang
Pertengahan tahun 2008 yang lalu, muncul polemik yang melibatkan pemerintah dan perusahaan tambang batu bara soal pembayaran royalti dan pajak tambang batu bara. Hal tersebut berawal dari pencekalan terhadap 14 direktur dan pengusaha tambang batu bara ke luar negeri. Langkah ini dilakukan pihak imigrasi atas permintaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Pangkal pencekalan ini adalah tidak disetornya royalti tambang batu bara oleh perusahaan tambang batu bara ke kas negara. Padahal, royalti batu bara merupakan bagian dana hasil produksi batu bara yang wajib disetorkan perusahaan kepada pemerintah. Sejak 2001 hingga 2007, royalti batu bara dan dana bagi hasil yang tidak dibayar perusahaan-perusahaan tambang itu besarnya mencapai sekitar Rp 7 triliun.
Namun, para pengusaha memiliki dalih mengapa mereka tak membayar royalti batu bara tersebut. Mereka merasa dirugikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000, yang menyatakan batu bara tidak lagi masuk kategori barang kena pajak pertambahan nilai (PPN). Adanya peraturan ini, menyebabkan perusahaan tambang batu bara tak bisa lagi mengalihkan pajak kepada para pembelinya.
Padahal, mereka tetap harus membayar pajak peralatan dan barang melalui pemasok atau vendor kepada negara. Menurut beberapa pengusaha tambang batu bara, beban inilah yang kemudian di set-off alias ditukar guling dengan potongan setoran royalti. Perusahaan tambang juga berdalih masih memiliki hak pengembalian pajak atau restitusi dari Departemen Keuangan sehingga mereka menahan pembayaran royalti.
Tetapi, pemerintah memiliki pandangan berbeda. Pemerintah menyatakan persoalan royalti dan permintaan restitusi pajak harus diperlakukan berbeda. Royalti merupakan piutang negara yang diperoleh dari hasil penjualan 13,5 persen batu bara bagian pemerintah yang dititipkan untuk dijual melalui perusahaan, ditambah dana pengembalian batu bara.
Permasalahan
Dalam sistem keuangan negara, royalti merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apa pun alasannya, perusahaan harus menyelesaikan masalah royalti ini. Sebab, membayar royalti merupakan kewajiban perusahaan berdasarkan kontrak pertambangan. Sedangkan restitusi pajak yang dituntut perusahaan tambang akibat adanya PP Nomor 144 tahun 2000, merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak.
Kasus restitusi pajak ini sendiri telah diproses melalui jalur hukum dan saat itu dalam tahap banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sikap ‘membandel’ yang dilakukan 14 perusahaan tambang batu bara dengan tetap tidak membayar royalti, mendorong pemerintah melakukan tindakan yang lebih keras. Pemerintah melakukan paksa badan atau gijzeling terhadap 14 petinggi perusahaan tersebut.
Bahkan, pemerintah juga mengeluarkan ancaman akan menutup izin operasi perusahaan yang menunggak pembayaran royalti. Ancaman ini mungkin dilaksanakan, mengingat terdapat beberapa hal yang memungkinkan pemerintah mencabut kontrak karya suatu perusahaan tambang. Pertama, apabila perusahaan tambang tidak mematuhi isi kontrak, terjadi tindak pidana. Kedua, jika kedua pihak bersepakat untuk mencabut kontrak.
Dalam konteks ini, pengusaha tambang batu bara menilai para pihak dalam kontrak tambang generasi pertama adalah pemerintah dan pengusaha. Artinya, PPN dan pembayaran royalti bukanlah dua sisi berbeda. Jadi, pemerintah dan pengusaha memiliki kewajiban yang sama-sama harus ditunaikan dan tidak ada yang perlu didahulukan. Sebab, kedua belah pihak butuh dana untuk proses pertumbuhan ekonominya.
Para pengusaha tambang menegaskan, jika pemerintah tetap memaksa perusahaan tambang batu bara untuk melunasi tunggakan royalti maka perusahaan-perusahaan akan menyatakan bangkrut. Oleh karena itu, pengusaha tambang batu bara meminta pemerintah untuk bersikap adil. Baik dalam menuntut maupun melunasi bagian yang seharusnya diterima perusahaan tambang.
Kronologi Penahanan Dana Hasil Penjualan Batu bara (DHPB)
Dalam sistem pengelolaan batu bara, terjadi beberapa kali perubahan aturan hukum. Perubahan aturan hukum ini kemudian berimplikasi pada perubahan sistem pajak, royalti, dan pungutan negara lainnya pada industri batu bara. Pada 1981-1983, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) ditandatangani, sering disebut sebagai PKP2B generasi pertama.
Dalam PKP2B ini, sistem pajak yang dianut adalah nail down. Jadi, apa yang menjadi kewajiban perpajakan dari kontraktor, telah diatur di dalam kontrak. Jika dalam perkembangannya ternyata ada pajak-pajak baru, pajak-pajak baru itu harus ditanggung pemerintah. Di dalam perjanjian PKP2B generasi pertama ini, para kontraktor selain membayar royalti dan sebagainya, mereka juga harus membayar pajak.
Jenis pajak yang harus dibayarkan perusahaan pertambangan batu bara berdasarkan PKP2B itu diantaranya adalah pajak perseroan, pajak deviden, pajak atas upah, upah pegawai kontraktor, IPEDA, bea materai, kemudian perusahan pertambangan batu bara juga dikenai pajak penjualan. Pada periode 1981, para kontraktor diwajibkan membayar pajak penjualan (PPn).
Selanjutnya pada 1983, terjadi perubahan di bidang perpajakan yaitu mulai berlakunya ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam kurun 1983 ini, pihak kontraktor tidak membayar pajak penjualan (PPn) tapi membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Industri batu bara membayar pajak pertambahan nilai, tetapi tidak membayar pajak penjualan.
Jadi, walapun di dalam kontrak telah diatur wajib membayar pajak pertambahan nilai, dengan keluarnya undang-undang tahun 1983, industri batu bara tidak membayar PPn, tetapi mereka membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Saat pajak PPN berlaku pada 1983, para kontraktor masih bisa meminta restitusi atas pajak masukan yang telah mereka bayarkan. Kemudian, kontraktor juga tidak mempermasalahkan kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, dihapuskannya pajak penjualan (PPn), pada tahun 1983 tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban perusahaan PKP2B untuk membayarnya (Kontrak bersifat ”Lex Specialis”).
Permasalahan royalti serta pungutan negara timbul pada 2001, yaitu dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000. Melalui PP ini, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang menyatakan bahwa batu bara bukan barang kena pajak (BKP). Padahal sebelumnya batu bara digolongkan sebagai BKP dan setelah 1 Januari 2001 PP tersebut berlaku efektif. Maka batu bara telah digolongkan sebagai barang bukan kena pajak (BBKP).
Akibat perubahan status komoditas itu, kontraktor PKP2B generasi pertama tidak dapat merestitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dibayar pada saat melakukan pembelian barang-barang dan jasa. Dengan diberlakukannya UU No. 18/2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM maka kontraktor PKP2B generasi pertama wajib membayar PPN atas perolehan BKP/JKP (jasa kena pajak), selain PPN atas perolehan JKP dalam negeri.
Kontraktor generasi pertama pun menahan pembayaran DHPB sebesar 13,5 persen yang menjadi bagian pemerintah, sebagai kompensasi restitusi PPN yang biasanya diterima sebelum 2001. Dana yang ditahan dalam kurun 2001-2005 mencapai Rp 3,85 triliun. Ini terjadi akibat perbedaan tafsir. Menurut Ditjen Pajak, batu bara adalah BBKP karena diambil langsung dari sumbernya. Bagi kontraktor, batu bara merupakan BKP sebab bernilai tambah atau jual melalui proses atau pengolahan.
Pada pasal 11 ayat 2 berkaitan dengan pajak penjualan, Ditjen Pajak melihat pajak penjualan sama dengan PPN, sebaliknya kontraktor melihat pajak penjualan tidak sama dengan PPN. Selama ini, kontribusi perusahaan batu bara ke kas negara berupa pajak perusahaan nett sebesar 45 persen ditambah 13,5 persen royalti dari gross (berarti dikalikan dua), dan pajak ekspor komoditas itu sebesar 5 persen sehingga totalnya mencapai 77 persen.
Diberlakukannya PP Nomor 144 tahun 2000 berakibat tidak adanya restitusi. Dengan demikian, kontraktor tidak bisa melakukan restitusi atas pajak masukannya. Ini yang menyebabkan kontraktor mulai mempermasalahkan pajak pertambahan nilai. Dalam perkembangannya, kontraktor menuntut restitusi PPN masukan melalui reimbursement, sebagaimana isi PKP2B. Namun Departemen ESDM tidak mempunyai mekanisme reimbursement.
Akibatnya, para kontraktor mulai mengambil posisi untuk menahan pembayaran DHPB-nya. Di sisi lain, ESDM mulai melakukan penagihan atas kewajiban kontraktor dalam kurun waktu 2001 hingga 2005. Namun, pengusaha batu bara bersikukuh tak bersedia membayar tunggakan DHPB-nya. Sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 2004 dan Undang-Undang No.49 Prp tahun 1960, Departemen ESDM menyerahkan tagihan piutang macetnya kepada panitia urusan piutang negara.
Hal ini sesuai dengan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), berdasar pasal 12 dan Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960, yakni diatur bahwa instansi-instansi pemerintah wajib menyerahkan piutang macetnya kepada PUPN. Kemudian ketika piutang itu diserahkan kepada PUPN, tentunya sebelum menerima, PUPN melakukan penelitian-penelitian terhadap dasar timbulnya piutang dan besarnya piutang.
Ternyata setelah diteliti oleh PUPN, penyerahan piutang macet dari Departemen ESDM itu sudah memenuhi syarat sebagai piutang negara, karena adanya syarat sebagai piutang negara bisa dibuktikan secara hukum, besarnya juga bisa ditetapkan secara hukum.
Kemudian setelah dinyatakan diterima, PUPN melakukan penagihan-penagihan. Dalam aktivitas penagihan ini, PUPN tentunya memperhatikan due process of law. Ini dilakukan dengan pemanggilan terhadap pengusaha batu bara untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Mereka datang ke PUPN dan menyatakan tidak bersedia membayar tunggakan DHPB. Sebab, mereka merasa mempunyai hak terhadap pemerintah berupa reimbursement atas PPN.
PUPN yang berpandangan telah meminta para pengusaha secara baik-baik untuk membayar kewajibannya kemudian melakukan sejumlah langkah lanjutan, sebagai respons keengganan para pengusaha memenuhi kewajiabnnya itu. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah mencegah para pengusaha tersebut bepergian ke luar negeri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Departemen Keuangan. Ini bertujuan agar para pengusaha batu bara tetap di Indonesia dan menyelesaikan kewajibannya.
Jika pencegahan telah dilakukan, pemerintah yakin para pengusaha batu bara tidak dapat ke luar negeri. Apalagi terdapat kontraktor yang berwarga negara asing. Dalam mengurus piutang ini pemerintah berpedoman pada tiga Undang-Undang (UU) yaitu UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Pasal-pasal penting yang digunakan diantaranya: ”…penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk di dalamnya kelompok PNBP. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.” Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. Jadi tidak dapat memanfaatkan sistem perjumpaan utang dan sebagainya. Dalam UU Nomor 1 tahun 2004, pasal yang penting adalah setiap pejabat wajib mengusahakan agar setiap piutang negara atau daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang menunggak atau menahan dana hasil produksi batu bara (Tabel 1):
Tabel 1. Para pengunggak DHPB

Perusahaan-perusahaan tersebut di atas adalah perusahaan PKP2B generasi pertama yang menahan pembayaran DHPB. Mereka adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo Coal (saat ini sudah tidak beroperasi). Dana hasil produksi batu bara (DHPB) adalah bagian pemerintah dari harga penjualan batu bara dengan total nilai keseluruhan 13,5 persen. DHPB terdiri atas royalti batu bara yang besarnya 5-7 persen tergantung kalori batu bara dan dana pengembangan batu bara sekitar 7,5 persen.
Namun, dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan penahanan DHPB. Hal ini misalnya seperti diungkapkan Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono. Jeffrey berpendapat, alasan pengusaha memotong DHPB, yang seharusnya disetor ke negara, adalah kompensasi dari pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara yang tidak dilakukan pemerintah.
Tindakan menahan DHPB sebagai kompensasi restitusi pajak berpangkal dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai perusahaan tambang batu bara yang paling awal masuk ke bisnis ini, seluruh PKP2B generasi pertama mendapat ketentuan sistem perpajakan yang tetap.
Dengan prinsip Lex Specialis itu, sepanjang masa kontraknya, perusahaan tidak terkena aturan pajak baru. Dalam kontrak juga disebutkan, jika muncul pajak baru yang sebelumnya tidak diproyeksikan, pemerintah akan membayar kembali nilai yang sama kepada kontraktor (reimbursement). Praktik ini berlangsung sampai keluarnya PP No 144/2000.
Dalam PP ini, pemerintah mengubah batu bara sebagai barang bukan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan batu bara generasi pertama tidak dapat mengenakan PPN keluaran pada penjualan batu baranya. Sementara perusahaan tetap menanggung seluruh PPN masukan atas semua barang, jasa, dan peralatan dalam produksi batu bara yang mereka miliki.
Sementara itu, PP No.144/2000 ini muncul karena protes perusahaan batu bara setelah generasi pertama yang tidak mendapat sistem perpajakan tetap sehingga mereka dikenai PPN batu bara. Besarnya PPN 8-9 persen itu dinilai memberatkan. Sejumlah upaya untuk mencari jalan keluar dari konsekuensi keluarnya PP No 144/2000 itu pernah ditempuh PKP2B generasi pertama dan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu yang diusulkan adalah mekanisme restitusi baru, tetapi pembicaraan terhenti.
Pada 2004, perusahaan-perusahaan batu bara generasi pertama melalui APBI, mengajukan uji materi atas PP No 144/2000 ke Mahkamah Agung (MA). MA berpendapat, secara substansi hukum, PP itu bertentangan dengan peraturan di atasnya. Namun, karena gugatan atas PP No 144/2000 yang diajukan asosiasi melampaui jangka waktu pengajuan 60 hari, putusan MA itu akhirnya hanya berupa fatwa atau imbauan. Fatwa MA itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah PP No 144/2000.
Selanjutnya, perusahaan batu bara generasi pertama tetap menyetorkan PPN barang dan jasa dari tahun 2001. Namun, berdasarkan perhitungan yang dibuat sendiri, mereka mengompensasinya dengan mengambil sebagian royalti yang merupakan kewajiban perusahaan ke pemerintah. Hal ini berlangsung sampai tahun 2007.
Departemen ESDM sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab atas DHPB mengaku sudah menegur perusahaan agar membayar kewajibannya. Royalti dan PPN adalah dua kewajiban yang berbeda. Namun, teguran itu tidak digubris. Setelah tujuh tahun, jumlah tunggakan mencapai Rp 7 triliun. Departemen ESDM pada pertengahan 2007 menyerahkan tagihan itu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negera (DJKN). DJKN menindaklanjutinya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Pada Juli 2007, PUPN mengeluarkan surat penetapan utang kepada setiap perusahaan. Perusahaan diberi waktu 1 x 24 jam untuk pelunasan. Apabila tidak ditaati, PUPN dapat mengeluarkan surat pencekalan, penyitaan aset, sampai penjualan aset. September 2007, enam perusahaan batu bara itu menggugat PUPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 3 Maret 2008, PTUN Jakarta menyatakan PUPN tidak berwenang memutuskan perselisihan antara perusahaan dan pemerintah.
PTUN memerintahkan PUPN membatalkan surat penetapan utang. Lalu, PUPN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 17 April 2008. Perdebatan yang muncul kemudian terkait tindakan DJKN, yang bertindak atas nama Menkeu, meminta pencekalan saat belum ada kekuatan hukum tetap dari perselisihan itu. Di sisi lain, tindakan perusahaan yang menahan DHPB selama bertahun-tahun tidak mendapat sanksi dari Departemen ESDM, sebagai pihak yang berkontrak mewakili pemerintah. (bersambung)
foto ilustrasi: itrademarket
*) Tentang Penulis:
Marwan Batubara, lahir di Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955. Marwan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mewakili provinsi DKI Jakarta. Menamatkan S1 di Jurusan Tehnik Elektro Universitas Indonesia dan S2 bidang Computing di Monash University (Australia). Marwan adalah mantan karyawan Indosat 1977-2003 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di Indosat. Melalui wadah Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N), ke depan Marwan berharap bisa berperan untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.