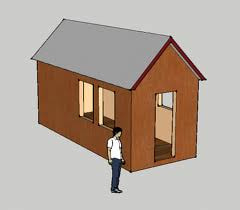Ada ucapan sederhana yang teramat dahsyat. Ia bisa menghancurleburkan gunung emosi. Ia juga mampu mencairkan kerasnya baja amarah. Dan, teramat cocok buat melunturkan noda-noda hasad. Ia cuma ucapan empat kata: “Maaf!”
Suasana hidup berkeluarga tak beda dengan pergaulan dalam masyarakat. Ada saatnya persentuhan melahirkan damai, tenang, membahagiakan. Tapi, ada saatnya menimbulkan gesekan. Terlebih ketika menyadari bahwa manusia tak mungkin luput dari salah dan khilaf. Siapa pun. Termasuk, suami, isteri, anak, bahkan mertua.
Masalahnya, tidak semua anggota rumah terlatih mengucapkan maaf. Karena ucapan yang terkesan sederhana ini tampaknya butuh kekuatan besar dalam jiwa. Perlu kerendahan hati untuk siap berbagi ego.
Seperti itulah yang dirasakan Bu Noni. Ibu satu anak ini kadang merasa bingung dengan suaminya. Ia heran, kenapa belum pernah terdengar ucapan maaf dari mulut suaminya. Walau sekali pun.
Padahal, hampir tiga tahun ia berumah tangga. Artinya, sudah lebih dari seribu hari ia hidup seatap dengan suaminya. Entah berapa jenis suka dan duka ia geluti bersama. Dan tentu saja, entah berapa kekhilafan yang pernah dilakukan antara ia dan suami. Atau, sebaliknya. Mulai dari hal-hal kecil seperti tak sengaja menyenggol vas bunga hingga pecah. Sampai, marah besar hanya karena persoalan anak-anak.
Namun, dari semua peristiwa, belum pernah keluar ucapan maaf. Seolah kesalahan itu seperti sebuah kewajaran. Seolah ketidaksengajaan menjadi hal lumrah dalam kehidupan berkeluarga. Seolah, seorang suami boleh berbuat salah. Tak ada yang dirugikan. Tak ada yang perlu dipersoalkan. Dan seolah, Bu Noni bertepuk sebelah tangan.
Buat Bu Noni, ucapan maaf sudah bukan barang mahal. Ia tak lagi merasa berat untuk bilang, “Maaf!” Kepada siapa pun: suami, anak, mertua, bahkan pembantu. Ia yakin, ucapan maaf bisa melunakkan ganjalan-ganjalan hati. Mungkin saja, seorang pembantu terlihat penurut. Pendiam. Tapi, karena persoalan ‘maaf’ yang terasa kecil itu, ia bisa menjadi bibit bom waktu. Suatu saat, bisa meledak.
Begitu pun dengan suami. Bu Noni sudah teramat biasa mengucapkan itu. Pernah ia mendapati suaminya yang meringis saat mencicipi sayur asam olahannya. Dengan segera, ia mendekati sang suami. “Eh, keasamannya, ya Yah! Maaf, ya!”
Bu Noni sangat menyadari kalau ungkapan sederhana itu bukan sekadar pelarian. Bukan basa-basi agar korban tidak lebih curiga atau marah. Bukan juga ungkapan ketundukan karena dilatari rasa takut, minder. Bukan itu. Justru, itulah ungkapan kehormatan yang keluar dari hati para pemberani. Bu Noni juga yakin, ungkapan maaf juga merupakan penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang Allah saja meninggikan nilai itu. Bahwa, kesalahan apa pun, disengaja atau tidak, besar atau kecil, bisa diartikan sebagai pengurangan hak seseorang.
Sebenarnya, Bu Noni ingin sekali bicara dari hati ke hati ke suami. Tapi, ia khawatir malah jadi salah sangka. Niat baik kalau salah terima bisa berakibat buruk. Kadang, Bu Noni jadi salah tingkah sendiri. Apa ada yang salah dengan dirinya. Karena boleh jadi, sikap suami seperti itu sebagai ungkapan protes.
Tapi rasa-rasanya, Bu Noni tak merasa pernah melakukan kesalahan fatal. Kalau pun pernah, ia langsung minta maaf. Dan permohonan maaf itu tak akan berhenti hingga ada jawaban dari suami. Paling tidak, ada senyum yang membalas.
Atau, jangan-jangan Bu Noni sendiri yang terlalu berperasaan. Bu Noni merenung dalam-dalam. “Benarkah begitu?” suara pelan berbisik dari balik lubuk hatinya yang dalam. Tapi, apa mungkin selama itu. Lagi pula, kalau pun memang teramat peka, Bu Noni bisa membedakan mana yang wajar dan mana yang agak lain.
Ah, hidup berumah tangga memang butuh kesabaran. Suara batin Bu Noni kembali menengahi, membangkitkan sebuah kesadaran. Boleh jadi, ia belum mengenal suaminya. Tiga tahun mungkin bukan waktu yang lama buat sebuah perkenalan.
Mungkin saja, sikap cuek dengan kesalahan kecil buat seseorang bukan menjadi masalah besar. Tergantung bagaimana pola asuh sejak kecil. Atau, ada takaran sendiri dalam lingkungan keluarga suami Bu Noni. Tentu akan sangat beda antara standar orang Betawi dengan Solo. Akan sangat beda antara Medan dengan Sunda.
Di situlah adaptasi berperan besar. Perkenalan yang baik akan berujung pada pemahaman yang pas tentang pasangan. Dan kunci dari semua itu adalah mau bicara terus terang. Apa yang dianggap salah. Apa yang dirasa mengganjal. Memang, perlu kecerdikan dan kesabaran agar alur komunikasi bisa berlangsung dua arah.
Masalahnya, mampukah Bu Noni melontarkan uneg-unegnya dengan baik dan benar. Bukan asal protes. Dan, segala sesuatu memang perlu seni. Termasuk dalam menjalin komunikasi. Boleh jadi, di situlah kelemahan Bu Noni. Ia mampu menampung uneg-uneg tanpa mengurangi kesabaran dan kesetiaan. Tapi, kurang sukses mengalirkannya tanpa beban.
Bu Noni kian tersadar. Kini, saatnya ia menata keharmonisan rumah tangganya dengan menghidupkan terus terang. Mungkin saja, sang suami tergolong pria yang mau bicara kalau diminta. Dan bukankah ini pembiasaan terbaik buat budaya rumah tangganya di masa depan. Saat ini ia yang mesti mulai bicara. Esok, mungkin suami dan anak.
Dan saat itulah, semua orang di keluarganya tak lagi menganggap remeh ucapan sederhana yang mampu mengubah hal besar. Agar tak ada lagi yang canggung atau merasa tidak perlu berucap, “Maaf! Saya memang salah!” ([email protected])