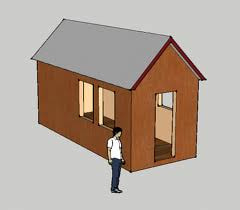Memenuhi idealisme pendidikan anak kadang tak ubahnya seperti menanti matahari. Malam terasa begitu panjang. Detik menyerupai jam, hari, bulan, bahkan tahun. Tapi, pagi tak kunjung datang. Kalau pun fajar menjelang, awan mendung kerap menghadang. Redup pagi menjadi kian temaram.
Tak ada orang tua yang rela anaknya tak berpendidikan. Pasti, siapa pun orang tua akan berupaya keras agar anaknya lebih baik dari dirinya. Paling tidak, tidak lebih buruk. Dalam hal apa pun: keimanan, akhlak, pengetahuan, keterampilan. Masalahnya, tidak semua orang tua tergolong mampu. Terutama, soal urusan keuangan.
Dari situlah, pertarungan berkobar. Sulit mengiyakan sebuah ungkapan yang mengatakan kalau pendidikan itu murah. Atau, pendidikan itu kewajiban negara dan hak warganya. Kenyataannya, anggaran bulanan buat satu anak di tingkat sekolah dasar saja bisa menyamai takaran umum anggaran belanja keluarga sepekan. Bahkan, bisa lebih. Bayangkan kalau anak yang sekolah bisa lebih dari tiga. Bayangkan juga kalau ketiga anak itu sekolahnya bukan lagi di sekolah dasar biasa. Tapi, sekolah dasar terpadu. Wah, pusiiing!
Itulah yang dialami Pak Dede. Bapak tiga anak ini kadang merasa bingung mesti berbuat apa. Penghasilan tetapnya tidak lebih dari biaya berlangganan lima belas koran sebulan. Tapi, biaya sekolah anak-anaknya bisa menyamai berlangganan sepuluh koran sebulan. Itu artinya, langganan lima koran sebulan sama dengan biaya hidup keluarga Pak Dede. Belum lagi buat biaya lain: kontrak rumah, listrik, ongkos. Kalau dihitung-hitung, defisit anggaran bisa mencapai separuh dari penghasilan tetapnya.
Kadang Pak Dede ragu mau berbuat apa. Penghematan sudah teramat ketat. Mau hemat gimana lagi. Sepertinya semua ruang gerak pengetatan sudah mentok. Itu pun sudah dibantu-bantu dengan penghasilan tambahan dari isteri: ngajar privat, jual obat suplemen, dagang jilbab. Cuma ada satu ruang yang sepertinya bisa diolah, tapi teramat dijaga Pak Dede: sekolah dasar terpadu.
Andai yang satu ini tidak masuk hitungan, anggaran keluarga Pak Dede mungkin bisa lebih longgar. Karena di sekolah anak inilah anggaran membengkak. Itu pun pada kondisi normal. Kalau ada biaya tambahan seperti sumbangan sekolah, studi wisata, pengambilan raport, daftar ulang, dan lain-lain, pembengkakan bisa di atas normal.
Namun, justru di sektor itu Pak Dede tidak mau bertoleransi. “Biar makan cuma pake garam, asal anak tetap di sekolah ideal,” ungkap Pak Dede ketika isterinya mengajak berpikir ulang soal sekolah anak-anak.
Ajakan sang isteri itu dilatarbelakangi masalah utang yang kian hari tambah lumayan. Justru, penyumbang utang terbesar jatuh pada biaya sekolah. Jarang pembayaran biaya sekolah anak-anak Pak Dede on time alias tepat waktu. Keseringannya nunggak. Kadang berseling satu bulan, sering juga dua hingga tiga bulan. Bahkan, pernah lebih dari enam bulan.
Musibah tunggakan terjadi ketika ada biaya-biaya lain yang minta lewat lebih dulu. Biasanya di soal kesehatan. Kalau ada yang sakit, ya mesti ke dokter. Dan kalau ke dokter, ya nggak bisa ngutang. Kalau sudah begitu, Pak Dede cuma bisa ngelus dada. “Ngutang lagi…, ngutang lagi!” Tentu saja, ngutangnya ke sekolah anak-anak, alias nunggak bayaran.
Kalau sudah begitu, Pak Dede merasa seperti dihimpit dua batu besar. Sesak sekali. Pernah ia benar-benar sedih. Ketika itu, anak sulungnya pulang sekolah dengan cemberut. Wajahnya ditekuk, mulutnya manyun, air mata tampak mulai menggenang. “Ada apa, Kak?” tanya Pak Dede. Yang ditanya tak bereaksi. Cuma cemberutnya yang makin jadi. “Ada apa?” tanya Pak Dede lagi lebih lembut. Tiba-tiba, tangis si sulung meledak. “Ayah sih, belum bayaran. Kakak ditegor-tegor nih sama Pak Guru!” sergah si sulung tak lagi tertahan. Seperti tak tertahannya perasaan pilu Pak Dede menatap air bening menitik lembut dari celah pipi puteri tercintanya.
Membayangkan pertarungan batin anak-anak yang terbentur bayaran, Pak Dede jadi prihatin. Anak-anaklah yang berhadapan langsung dengan sekolah. Tiap hari, tiap jam, tiap saat. Ah, betapa malu anak-anak setiap kali menatap guru selalu teringat bayaran. Sulit membayangkan bagaimana perasaan mereka. Gimana daya serap mereka dengan pelajaran kalau peraasan sudah tak karuan. Kalau guru menghampiri, rasa was-was timbul tenggelam. Udah bayaran apa belum, ya? Yah, ditegur lagi, deh. Begitulah mungkin perasaan anak-anak.
Andai teguran sang guru kepada anak-anak berkenaan dengan prestasi belajar. Andai panggilan khusus menyangkut masalah penghargaan mutu belajar. Bukan yang mereka alami seperti sekarang ini, soal bayaran. “Ah, benar-benar menyakitkan,” suara batin Pak Dede demi membayangkan warna-warni perasaan anak-anaknya.
Lebih jauh, Pak Dede kadang sepintas menyaksikan bagaimana teman-teman sekolah anaknya. Ada yang diantar jemput dengan mobil bagus. Ada yang bersepatu mahal. Ada yang berjam tangan merek terkenal. Bahkan, ada juga yang membawa telepon genggam mahal. “Ah, gimana perasaan anak-anakku. Maafkan aku, Nak!” lagi-lagi bisik batin Pak Dede menyadarkan lamunannya.
Bukan pada tempatnya kalau ia menyalahkan pihak sekolah yang menentukan biaya sekolah ratusan ribu rupiah per bulan. Investasi pendidikan memang mahal. Sementara modal keuangan lembaga Islam begitu terbatas.
Begitu pun, bukan saatnya lagi, Pak Dede meminta-minta dikasih keringanan. Karena ini menjadi dilema buat lembaga Islam yang mulai ingin berkembang: dikasih mengurangi investasi, nggak dikasih mengganggu kesehatan berukhuwah. Dan bayangkan, kalau yang minta keringanan bukan cuma Pak Dede.
Kalau keringanan buat lebih dari satu Pak Dede ditambah lagi dengan ‘musibah’ nunggak, wah, jangan-jangan bisa berimbas buat para guru. Boleh jadi, karena modal terbatas, dua kasus itu menghambat para guru nerima gajian on time. Dengan kata lain, guru-guru yang sudah capek ngajar mesti mensubsidi ketidakmampuan orang-orang seperti Pak Dede.
Pak Dede kian termenung. Ia tahu betul berapa gaji guru sekolah dasar. Walau sekolah terpadu sekali pun. Itulah yang pernah ia dengar dari teman dekatnya. Gaji mereka belum mampu menjangkau banyak hal. Termasuk, menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah dasar terpadu.
Mengenang cerita teman dekatnya, Pak Dede menemukan kesadaran baru. Memang, zhalim orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang ideal. Tapi, akan lebih zhalim lagi jika para guru yang akhirnya mesti menanggung. Mereka harus menunda bahagia, karena gaji belum bisa diterima. “Ah, hidup memang bukan fatamorgana,” ujar Pak Dede menangkap bayang-bayang baru. ([email protected])